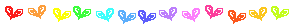Pertanyaan :
Seseorang memiliki tanggungan/hutang beberapa hari puasa Ramadhan. Namun hingga datang bulan Ramadhan tahun berikutnya ternyata ia belum juga mengqodho’ (mengganti kewajiban/membayar) hutang puasanya tersebut. Bagaimana seharusnya yang ia lakukan? Apakah ia berdosa, dan apakah gugur kewajibannya?
Jawab :
Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur`anul Karim :
(( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))
“Barangsiapa diantara kalian yang mendapati bulan (Ramadhan) maka hendaklah ia berpuasa, dan barangsiapa yang sakit atau berpergian (lalu ia tidak berpuasa) maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari yang lain.”Al Baqorah : 185.
Sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika ada alasan syar’i, kemudian ia berkewajiban untuk menggantinya pada hari-hari lain, serta tidak menundanya sampai datang bulan Ramadhan berikutnya, dengan dasar ucapan ‘Aisyah Radhiyallah ‘anha (istri Rasulullah), ia berkata :
كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ .
Dahulu kami memiliki tanggungan/hutang puasa Ramadhan, dan tidaklah aku sempat mengqodho’nya (yakni terus tertunda) kecuali setelah sampai bulan Sya’ban (yakni terus tertunda hingga tiba bulan Sya’ban berikutnya). (HR. Al-Bukhari, Bab Kapan Menunaikan Qodho’ Puasa, no.1950)
‘Aisyah Radhiyallah ‘anha tidak sempat mengqodho’ puasanya hingga tiba bulan Sya’ban (berikutnya) karena keadaan beliau di sisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam .
Adapun perkataan Aisyah : “dan tidaklah aku sempat mengqodho’nya kecuali setelah sampai bulan Sya’ban”, adalah dalil wajibnya mengqodho’ puasa Ramadhan sebelum datang bulan Ramadhan berikutnya.
Namun apabila qodho’nya diakhirkan/ditunda-tunda hingga datang bulan Ramadhan tahun berikutnya maka ia berkewajiban untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, serta menyesal dan mencela perbuatannya menunda-nunda qodho’ puasa. Namun ia tetap berkewajiban mengqodho’ puasanya yang ia tinggalkan, karena kewajiban mengqodho’ tidak gugur dengan sebab diakhirkan/ditunda. Maka ia tetap wajib menggantinya walaupun setelah bulan Ramadhan tahun berikutnya,Wallahul Muwaffiq.
Fatawa Arkanul Islam oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, halaman 489, pertanyaan yang ke - 439.
http://www.assalafy.org/mahad