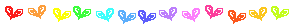Membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis memang menjadi dambaan. Namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan mudah. Butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu agama. Sesuatu yang mesti dipunyai seorang istri, terlebih sang suami.
Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa menikah berarti menjalani hidup baru. Karena dalam kehidupan pasca pernikahan memang dijumpai banyak hal yang sebelumnya tidak didapatkan saat melajang. Tentunya semua itu bisa dirasakan oleh mereka yang telah membangun mahligai rumah tangga.
Pernikahan juga merupakan kehidupan orang dewasa. Sebab, banyak hal yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan pikiran orang yang dewasa, bukan dengan pikiran kanak-kanak. Masalah hubungan suami istri, pendidikan anak, ekonomi keluarga, hubungan kemasyarakatan, dan lain sebagainya, mau tidak mau akan hadir dalam kehidupan mereka yang telah berkeluarga.
Maka, tidak salah pula bila dikatakan untuk menikah itu butuh ilmu syar‘i, baik pihak istri, terlebih lagi pihak suami sebagai qawwam (pemimpin) bagi keluarganya.Karena dengan ilmu yang disertai amalan, akan tegak segala urusan dan akan lurus jalan kehidupan. Namun sangat disayangkan, sisi yang satu ini sering luput dari persiapan dan sering terabaikan, baik sebelum pernikahan terlebih lagi pasca pernikahan.
Pendidikan Keluarga
Allah Azza wa Jalla berfirman:
“Kaum laki-laki (suami) adalah qawwam (pemimpin) bagi kaum wanita (istri).? (An-Nisaa’: 34)
Salah satu tugas suami sebagai qawwam adalah memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, meluruskan mereka dari penyimpangan, dan mengenalkan mereka kepada kebenaran. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.? (At-Tahrim: 6)
Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat yang mulia ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhaanahu wa Ta’aala, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya. Seorang suami wajib mengajari keluarganya tentang perkara yang di-fardhu-kan oleh Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Bila ia mendapati mereka berbuat maksiat segera dinasehati dan diperingatkan. (Tafsir Ath-Thabari, 28/166, Ruhul Ma‘ani, 28/156)
Asy-Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa`di rahimahullah berkata: “Menjaga jiwa dari api neraka bisa dilakukan dengan mengharuskan jiwa tersebut untuk berpegang dengan perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan bertaubat dari perkara yang mendatangkan murka dan adzab-Nya. Di samping itu, menjaga istri dan anak-anak dilakukan dengan cara mendidik dan mengajari mereka, serta memaksa mereka untuk taat kepada perintah Allah. Seorang hamba tidak akan selamat kecuali bila ia menegakkan perkara Allah pada dirinya dan pada orang-orang yang berada di bawah perwaliannya seperti istri, anak-anak, dan selain mereka.? (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 874)
Ayat ini menunjukkan wajibnya suami mengajari anak-anak dan istri tentang perkara agama dan kebaikan serta adab yang dibutuhkan. Hal ini semisal dengan firman Allah Azza wa Jalla � kepada Nabi-Nya Shallallaahu ‘alaihi wasallam :
“Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam menegakkannya.? (Thaha: 132)
“Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat.? (Asy-Syu`ara: 214)
Ini menunjukkan keluarga yang paling dekat dengan kita memiliki kelebihan dibanding yang lain dalam hal memperoleh pengajaran dan pengarahan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. (Ahkamul Qur’an, 3/697)
Malik Ibnul Huwairits radiyallahu ‘anhu mengabarkan: “Kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam dan ketika itu kami adalah anak-anak muda yang sebaya. Lalu kami tinggal bersama beliau di kota Madinah selama sepuluh malam. Kami mendapati beliau Shallallaahu ‘alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang lagi lembut. Saat sepuluh malam hampir berlalu, beliau menduga kami telah merindukan keluarga kami karena sekian lama berpisah dengan mereka. Beliau pun bertanya tentang keluarga kami, maka cerita tentang mereka pun meluncur dari lisan kami. Setelahnya beliau Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah di tengah mereka dan ajari mereka, serta perintahkanlah mereka.? (Shahih, HR. Al-Bukhari no. 628 dan Muslim no. 674)
Dalam hadits di atas, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada shahabatnya untuk memberikan taklim (pengajaran) kepada keluarga dan menyampaikan kepada mereka ilmu yang didapatkan saat bermajelis dengan seorang ‘alim.
Dengan penjelasan yang telah lewat, dapat dipahami bahwa seorang suami/ kepala rumah tangga harus memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anak istrinya, mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan menjauhkan mereka dari penyimpangan.
Namun sangat disayangkan, kenyataan yang kita lihat banyak kepala keluarga yang melalaikan hal ini. Yang ada di benak mereka hanyalah bagaimana mencukupi kebutuhan materi keluarganya sehingga mereka <span>tenggelam dalam perlombaan mengejar dunia</span>, sementara kebutuhan spiritual tidak masuk dalam hitungan. Anak dan istri mereka hanya dijejali dengan harta dunia, bersenang-senang dengannya, namun bersamaan dengan itu mereka tidak mengerti tentang agama.
Paling tidak, bila seorang suami tidak bisa mengajari keluarganya, mungkin karena kesibukannya atau keterbatasan ilmunya, ia mencarikan pengajar agama untuk anak istrinya, atau mengajak istrinya ke majelis taklim, menyediakan buku-buku agama, kaset-kaset ceramah/ taklim sesuai dengan kemampuannya, dan menganjurkan keluarganya untuk membaca/ mendengarnya.
Mendidik Istri
Memasuki masa-masa awal pernikahan, semestinya seorang suami telah merencanakan pendidikan agama bagi istrinya. Minimalnya ia mempunyai pandangan ke arah sana. Dan sebelum menjadi seorang ayah, semestinya ia telah menyiapkan istrinya untuk menjadi pendidik anak-anaknya kelak karena:
“Ibu adalah madrasah (sekolah) bagi anak-anaknya?, kata penyair Arab.
Perlu juga diperhatikan, bahwa mendapatkan pengajaran agama termasuk salah satu hak istri yang seharusnya ditunaikan oleh suami dan termasuk hak seorang wanita yang harus ditunaikan walinya. Namun pada prakteknya, hak ini seringkali tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehingga tepat sekali ucapan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi‘i rahimahullah yang membagi manusia menjadi tiga macam dalam mengurusi wanita:
Pertama: <span>Mereka yang melepaskan wanita begitu saja sekehendaknya</span>, membiarkannya bepergian jauh tanpa mahram, bercampur baur di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, di tempat kerja seperti kantor dan di rumah sakit. Sehingga mengakibatkan rusaknya keadaan kaum muslimin.
Kedua: <span>Mereka yang menyia-nyiakan wanita tanpa taklim</span> (pengajaran), membiarkannya seperti binatang ternak, sehingga ia tidak tahu sedikit pun kewajiban yang Allah bebankan padanya. Wanita seperti ini akan menjatuhkan dirinya kepada fitnah dan penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah Subhaanahu wa Ta’aala, bahkan akan merusak keluarganya.
Ketiga: <span>Mereka yang memberikan pengajaran agama kepada wanita sesuai dengan kandungan Al Qur’an dan As Sunnah</span>, karena melaksanakan perintah Allah Subhaanahu wa Ta’aala :
“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.? (At- Tahrim: 6)
Dan karena Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya/ dimintai tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya.? (Shahih, HR. Al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)(Nashihati lin Nisa’, Ummu ‘Abdillah Al-Wadi`iyyah, hal. 7-8)
Seorang istri perlu diajari tentang perkara yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari, siang dan malamnya, tentang tauhid, bahaya syirik, maksiat dan penyakit-penyakit hati berikut pengobatannya. Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam sendiri menyediakan waktu khusus untuk mengajari para wanita. Abu Sa’id Al-Khudri radiyallahu ‘anhu berkata: “Datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, lalu ia berkata:
“’Wahai Rasulullah! Kaum laki-laki telah pergi membawa haditsmu, maka berikanlah untuk kami satu hari yang khusus di mana kami dapat mendatangimu untuk belajar kepadamu dari ilmu yang Allah telah ajarkan padamu.’ Beliau pun bersabda: ‘Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu di tempat ini (yakni beliau menyebutkan waktu dan tempat tertentu)’. Hingga mereka pun berkumpul pada hari dan tempat yang dijanjikan untuk mengambil ilmu dari beliau sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada beliau.? (Shahih, HR. Al-Bukhari no. 101 dan Muslim no. 2633)
Bahkan istri-istri Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam “lahir? dari madrasah nubuwwah dan mereka menuai bekal ilmu yang banyak terutama Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu ‘anha yang besar dalam asuhan madrasah yang mulia ini. Sepeninggal suami mereka, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, mereka menjadi pendidik umat bersama dengan para shahabat yang lain, semoga Allah meridhai mereka.
Gambaran Pengajaran Seorang ‘Alim terhadap Keluarga Mereka
Para pendahulu kita yang shalih (salafunash shalih) sangat mementingkan pendidikan agama bagi keluarga mereka. Di samping mereka berdakwah kepada umat di luar rumah, mereka juga tidak melupakan orang-orang yang berada dalam rumah mereka (keluarga). Tidak seperti kebanyakan manusia pada hari ini yang sibuk dengan urusan mereka di luar rumah sehingga melalaikan pendidikan istrinya.
Bahkan sangat disayangkan hal ini juga menimpa keluarga da‘i. Ia sibuk berdakwah kepada masyarakatnya sementara istrinya di rumah tidak mengerti tata cara shalat yang diajarkan oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, tidak tahu cara menghilangkan najis, dan sebagainya. Yang lebih parah, istri atau anaknya tidak mengerti tentang tauhid dan syirik. Bandingkan dengan apa yang ada pada salaf!
Lihatlah keluarga Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullah. Beliau demikian bersemangat menyebarkan ilmu di tengah keluarganya dan kerabatnya sebagaimana semangatnya menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kesibukan beliau dalam dakwah di luar rumah dan dalam menulis ilmu tidaklah melalaikan beliau untuk memberi taklim kepada keluarganya. Dari hasil pendidikan ini lahirlah dari keluarga beliau orang-orang yang terkenal dalam ilmu khususnya ilmu hadits, seperti: saudara perempuannya Sittir Rakb bintu ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar Al-’Asqalani, istrinya Uns bintu Al-Qadhi Karimuddin Abdul Karim bin ‘Abdil ‘Aziz, putrinya Zain Khatun, Farhah, Fathimah, ‘Aliyah, dan Rabi`ah. (Inayatun Nisa bil Haditsin Nabawi, hal. 126-127)
Lihat pula bagaimana Sa’id Ibnul Musayyab rahimahullah membesarkan dan mengasuh putrinya dalam buaian ilmu hingga ketika menikah suaminya mengatakan ia mendapati istrinya adalah orang yang paling hapal dengan kitabullah, paling mengilmuinya, dan paling tahu tentang hak suami. (Al-Hilyah, 2/167-168, As-Siyar, 4/233-234)
Demikian pula kisah keilmuan putri Al-Imam Malik rahimahullah. Dengan bimbingan ayahnya, ia dapat menghapal Al-Muwaththa’ karya sang Imam. Bila ada murid Al-Imam Malik membacakan Al-Muwaththa’ di hadapan beliau, putrinya berdiri di belakang pintu mendengarkan bacaan tersebut. Hingga ketika ada kekeliruan dalam bacaan ia memberi isyarat kepada ayahnya dengan mengetuk pintu. Maka ayahnya (Al-Imam Malik) pun berkata kepada si pembaca: “Ulangi bacaanmu karena ada kekeliruan?. (Inayatun Nisa’, hal. 121)
Perhatian pendahulu kita rahimahumullah terhadap pendidikan keluarganya ternyata juga kita dapatkan dari ulama yang hidup di zaman kita ini, seperti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi‘i rahimahullah. Dalam sehari beliau menyempatkan waktu untuk mengajari anak istrinya tentang perkara-perkara agama yang mereka butuhkan, hingga mereka mapan dalam ilmu dan dapat memberi faedah kepada saudara mereka sesama muslimah dalam majelis yang mereka adakan atau dari karya tulis yang mereka hasilkan. Demikian kisah ulama kita dengan keluarganya, lalu di mana tempat kita bila dibanding dengan mereka ?
Wallahu ta‘ala a‘lam bish-shawab.
Sumber : <span>www.asysyariah.com, Penulis: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah</span>