Pembahasan kali ini adalah kelanjutan artikel hadiah di hari lahir. Saat ini kita akan masuk pada pembahasan aqiqah. Untuk serial aqiqah pertama ini, kami angkat pembahasan seputar hukum aqiqah dan siapa yang dituntut melaksanakan aqiqah. Semoga bermanfaat.
Pengertian Aqiqah
Mengenai pengertian aqiqah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama –semisal dalam kitab fiqh Syafi’iyah-, yaitu aqiqah berasal dari kata (عَقَّ يَعِقُّ). Secara bahasa, aqiqah adalah sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir. Sedangkan secara istilah, aqiqah berarti sesuatu yang disembelih ketika menggundul kepala si bayi. Aqiqah dinamakan dengan sebabnya karena menyembelihnya berarti (يُعَقُّ), yaitu memotong, sedangkan rambut kepala si bayi dicukur pula ketika itu.[1]
Pensyariatan Aqiqah
Aqiqah adalah sesuatu amalan yang disyari’atkan oleh kebanyakan ulama semacam Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah, para fuqoha tabi’in, dan para ulama di berbagai negeri. Dalil pensyariatan aqiqah adalah sebagai berikut.
Pertama: Hadits Salman bin ‘Amir.
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى »
“Dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya dan hilangkan gangguan darinya." (HR. Bukhari no. 5472)
Kedua: Hadits Samuroh bin Jundub.
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »
Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama." (HR. Abu Daud no. 2838, An Nasai no. 4220, Ibnu Majah nol. 3165, Ahmad 5/12. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)
Ketiga: Hadits –Ummul Mukminin- ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَأُمِّ كُرْزٍ وَبُرَيْدَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَسَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَفْصَةُ هِىَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
Dari Yusuf bin Mahak, mereka pernah masuk menemui Hafshah binti 'Abdirrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum aqiqah. Hafshah mengabarkan bahwa 'Aisyah pernah memberitahu dia, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammemerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang hampir sama (umurnya[2]) untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan."
Ia berkata, "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ali dan ummu Kurz, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata, "Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih, sementara maksud Hafshah dalam hadits tersebut adalah (Hafshah) binti 'Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq." (HR. Tirmidzi no. 1513. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih)
Keempat: Hadits Ibnu ‘Abbas.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.
Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengaqiqahi Al Hasan dan Al Husain, masing-masing satu ekor gibas (domba jantan).” (HR. Abu Daud no. 2841. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih[3])
Hukum Aqiqah
Setelah kita melihat hadits-hadits tentang pensyariatan aqiqah di atas, lantas apakah hukum aqiqah itu sendiri? Wajib ataukah sunnah?
Mengenai masalah ini, para ulama terdapat silang pendapat.
Berdasarkan hadits,
مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
“Dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya" (HR. Bukhari no. 5472), juga berdasarkan hadits lainnya, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum aqiqah itu wajib semacam ulama Zhohiriyah (Daud, Ibnu Hazm, dkk), dan Al Hasan Al Bashri. Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum aqiqah itu tidak wajib dan juga tidak sunnah. –Demikian dikatakan oleh Asy Syaukani dalam Nailul Author-[4]
Hadits dari jumhur ulama yang menyatakan hukum aqiqah adalah sunnah berpegang pada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ
“Barangsiapa yang senang untuk mengaqiqahi anaknya, maka lakukanlah.”[5] Hadits ini menunjukkan bahwa aqiqah itu tidak wajib karena di sini dikatakan boleh memilih. Dalil ini adalah indikasi yang memalingkan perintah yang disebutkan dalam hadits-hadits yang memerintahkan aqiqah kepada perintah sunnah.[6]
Lalu bagaimana dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang menyatakan bahwa hukum aqiqah tidak wajib dan tidak pula sunnah?
Ibnul Mundzir –sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Al Fath- mengatakan, “Ulama Hanafiyah (ashabur ro’yi) yang mengingkari sunnahnya aqiqah telah menyelisihi hadits-hadits shahih mengenai hal ini. Sebagian mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Malik dalam Al Muwatho’ dari Zaid bin Aslam dari seorang Bani Dhomroh dari ayahnya, ia menanyakan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai aqiqah. Jawaban Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
لَا أُحِبّ الْعُقُوق
“Aku tidak menyukai aqiqah”, seakan-akan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyukai penamaan aqiqah. Lalu beliau bersabda,
مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَد فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسَك عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ
Dalam riwayat Sa’id bin Manshur, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam dari seorang Bani Dhomroh dari pamannya, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai aqiqah sedangkan beliau di mimbar di Arofah, lalu beliau menyebutkan semacam tadi.” Hadits ini pun memiliki penguat dari hadits ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dikeluarkan oleh Abu Daud. Dua hadits ini dikuatkan satu dan lainnya. Abu ‘Umr mengatakan, “Aku tidak mengetahui hadits tersebut marfu’ (sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) kecuali dari dua riwayat ini.” Al Bazzar dan Abusy Syaikh juga telah mengeluarkan hadits tentang aqiqah dari Abu Sa’id, namun hadits tersebut bukanlah jadi hujjah bagi yang menyatakan tidak disyari’atkannya aqiqah. Bahkan akhir hadits jelas-jelas menetapkan disyariatkannya aqiqah. Sedangkan yang dimaksud dalam hadits adalah lebih utama menyebut aqiqah dnegan nasikah atau dzabihah, dan dilarang menyebutnya dengan aqiqah. Telah dinukil dari Ibnu Abid Dam dari beberapa sahabat mengenai penamaan semacam ini sebagaimana tidak disukai pula menyebut Isya dengan ‘atamah.”[8]
Kesimpulan: Aqiqah adalah suatu yang disyariatkan tidak sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. Hukumnya berkisar antara wajib dan sunnah. Sedangkan kami sendiri lebih cenderung pada pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan hukum aqiqah adalah sunnah. Namun sudah sepantasnya bagi orang yang mampu yang diberi kelebih rizki oleh Allah Ta’alatidak meninggalkan syari’at yang mulia ini.
Sayyid Sabiq -rahimahullah- memiliki perkataan yang amat baik. Beliau berkata, “Hukum aqiqah adalah sunnah muakkad(sunnah yang amat dianjurkan), walaupun si ayah (yang membiayai aqiqah) adalah orang yang dalam keadaan sulit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tetap melakukan aqiqah , begitu pula sahabatnya. Telah diriwayatkan oleh penyusun kitab sunan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengaqiqahi Al Hasan dan Al Husain masing-masing dengan satu ekor kambing. Sedangkan ulama yang mewajibkan aqiqah adalah Al Laits dan Daud Azh Zhohiri.”[9]
Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jika si ayah dalam keadaan sulit sekalipun hendaklah melakukan aqiqah. Apa yang beliau utarakan senada dengan perkataan Imam Ahmad -rahimahullah-. Imam Ahmad pernah berkata,
إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَعُقُّ ، فَاسْتَقْرَضَ ، رَجَوْت أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إحْيَاءَ سُنَّةٍ .
“Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengaqiqahi (buah hatinya), maka hendaklah ia mencari utangan. Aku berharap ia mendapatkan ganti di sisi Allah karena ia berarti telah menghidupkan ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”[10]
Manfaat Aqiqah
Dalam hadits disebutkan,
كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ
“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya.”
Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud hadits di atas. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seorang anak tidak diaqiqahi, dia tidak akan memberikan syafa’at kepada kedua orang tuanya.[11]
Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin juga pernah menjelaskan maksud hadits di atas. Beliau –rahimahullah- mengatakan,
“Sebagian ulama mengartikan “setiap anak digadaikan dengan aqiqahnya” bahwasanya aqiqah adalah sebab anak tersebut terlepas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Hatinya akan begitu lapang setelah diaqiqahi. Jika seorang anak tidak diaqiqahi maka keadaannya akan selalu gelisah layaknya orang yang berutang dan menggadaikan barangnya. Inilah pendapat yang lebih tepat tentang maksud hadits tersebut. Jadi, aqiqah adalah sebab seorang anak akan mendapatkan kemaslahatan, hatinya pun tidak begitu gelisah dan semakin mudah dalam aktivitasnya.”[12]
Siapa yang Dituntut Melaksanakan Aqiqah?
Aqiqah dituntut pada ayah selaku penanggung nafkah. Aqiqah ini diambil dari harta ayah dan bukan harta anak. Selain ayah boleh menanggung biaya aqiqah, namun dengan seizin ayahnya.
Sebagaimana disebutkan dalam Subulus Salam, Ash Shon’ani -rahimahullah- mengatakan, “Menurut Imam Asy Syafi’i, aqiqah itu dituntut dari setiap orang yang menanggung nafkah si bayi. Sedangkan menurut ulama Hambali, aqiqah itu dituntut khusus dari ayah, kecuali jika ayahnya tersebut mati atau terhalang tidak bisa memenuhi aqiqah.”[13]
Dalam masalah ini berarti ada perselisihan pendapat, siapakah yang dituntut melaksanakan aqiqah. Namun tentu saja yang utama adalah ayah yang menanggung biaya ini, apalagi ayahlah yang sudah jelas penanggung nafkah keluarga. Sehingga kurang tepat jika aqiqah dibebankan pada anak atau ibu yang sama sekali bukan orang yang bertanggung jawab mencari nafkah keluarga. Wallahu a’lam.
Lalu bagaimanakah dengan aqiqah yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap cucunya –Al Hasan dan Al Husain-?
Dijawab oleh salah seorang ulama Syafi’iyah, Asy Syarbini -rahimahullah-, “Aku jawab bahwa yang dimaksud dengan aqiqah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada keduany adalah perintah beliau kepada kedua orang tuanya, atau boleh jadi pula beliau yang memberikan hewan yang akan dijadikan aqiqah, atau barangkali lagi Al Hasan dan Al Husain menjadi tanggungan nafkah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena kedua orang tua mereka adalah orang yang kurang mampu. Namun jika aqiqah itu diambil dari harta anak, maka itu tidak dibolehkan bagi wali (orang tua) untuk melakukannya. Karena aqiqah itu termasuk pemberian cuma-cuma (tabarru’) dari orang tua sehingga tidak boleh hewan aqiqah diambil dari harta anak. ”[14]
Bagaimana Jika Tidak Mampu Aqiqah? Apakah Harus Mengaqiqahi Diri Sendiri Ketika Dewasa?
Aqiqah tentu saja melihat pada kemampuan orang yang bertanggung jawab untuk aqiqah. Karena Allah Ta’ala berfirman,
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian” (QS. At Taghobun: 16).
Asy Syarbini –rahimahullah- menjelaskan, “Jika orang tua tidak mampu melakukan aqiqah pada saat kelahiran, namun setelah itu ia mendapati kemudahan pelaksanaan aqiqah sebelum hari ketujuh kelahiran, maka ketika itu ia disunnahkan melaksanakan aqiqah. Jika orang tua mendapati kemudahan pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh dan masih tersisa sedikit waktu istri mengalami nifas, maka sebagian ulama belakangan tidak memerintahkan untuk dilaksanakan aqiqah. Akan tetapi ulama Syafi’iyah menganjurkan dilaksanakannya aqiqah jika masih dalam masa nifas, inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al Anwar.”[15]
Lalu bagaimana jika bayi sebenarnya mampu diaqiqahi ketika lahir, namun sampai dewasa, ia belum juga diaqiqahi?
Menurut ulama Syafi’iyah, orang tua yang mampu mengaqiqahi, ia tetap dianjurkan mengaqiqahi anaknya meskipun anaknya sudah dewasa. Jika sampai dewasa, anak tersebut belum juga diaqiqahi, maka ia boleh mengaqiqahi dirinya sendiri. Sedangkan sebagian orang yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengaqiqahi dirinya sendiri setelah diangkat sebagai Nabi, dalam Al Majmu’ disebut sebagai pendapat yang batil.[16]
Sebagaimana pula dikatakan dalam salah satu kitab ulama Syafi’iyah, Kifayatul Akhyar, “Riwayat yang menyatakan bahwa Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam mengaqiqahi dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Nabi adalah riwayat yang dho’if (lemah) dari setiap jalannya.”[17]
Pendapat yang bagus tentang masalah ini diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin. Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau –rahimahullah-, “Apabila seseorang tidak diaqiqahi ketika kecil, apakah ia tetap dianjurkan untuk diaqiqahi ketika dewasa? Apa saja batasan masih dibolehkannya aqiqah?”
Beliau -rahimahullah- memberikan jawaban –di antaranya-,
“Apabila orang tuanya dahulu adalah orang yang tidak mampu pada saat waktu dianjurkannya aqiqah, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa walaupun mungkin setelah itu orang tuanya menjadi kaya. Sebagaimana apabila seseorang miskin ketika waktu pensyariatan zakat, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, meskipun setelah itu kondisinya serba cukup. Jadi apabila keadaan orang tuanya tidak mampu ketika pensyariatan aqiqah, maka aqiqah menjadi gugur karena ia tidak memiliki kemampuan.
Sedangkan jika orang tuanya mampu melaksanakan aqiqah ketika ia lahir, namun ia menunda aqiqah hingga anaknya dewasa, maka pada saat itu anaknya tetap diaqiqahi walaupun sudah dewasa.”[18]
Intinya, untuk masalah ini kembali ke kemampuan sang ayah ketika bayi itu lahir. Jika ayahnya di hari kelahiran termasuk orang yang tidak mampu untuk melaksanakan aqiqah, maka aqiqahnya jadi gugur termasuk pula ketika ia dewasa. Sedangkan jika sang ayah adalah orang yang mampu ketika itu, maka sampai dewasa pun si anak dituntut untuk diaqiqahi. Adapun jika si anak mengaqiqahi dirinya ketika dewasa, maka ini pendapat yang perlu dikritisi. Karena Imam Asy Syafi’i sendiri menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah mengaqiqahi dirinya sendiri (ketika dewasa) sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab fiqih Syafi’iyah Kifayatul Akhyar[19].Wallahu a’lam.
Pembahasan aqiqah tidak hanya sampai di sini, kita masih melanjutkan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan aqiqah. Semoga Allah mudahkan.
Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi wa taimmush sholihaat.
Artikel www.rumaysho.com
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal
Panggang-GK, 25 Jumadits Tsani 1431 H, 07/06/2010
[1] Lihat Mughnil Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhi Al Minhaj (Kitab Syarh Minhaj Ath Tholibin), Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini, 4/390, Darul Ma’rifah, cetakan pertama, 1418 H.
[2] Sebagaimana keterangan dari Sayyid Sabiq dalam catatan kaki kitab Fiqh Sunnah, 3/327, Darul Kutub Al ‘Arobi, Beirut-Lebanon.
[3] Namun pembahasan mengenai hadits ini -insya Allah- akan disinggung selanjutnya pada pembahasan “hewan yang diaqiqahi” dalam tulisan serial kedua.
[4] Nailul Author, Muhammad bin ‘Ali Asy Syaukani, 8/154, Mawqi’ Al Waroq.
[5] HR. Ahmad 2/182. Syaikh Syu’aib Al Arnauth menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan.
[6] Nailul Author, 8/154.
[8] Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqolani, 9/588, Darul Ma’rifah, 1379.
[9] Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 3/326, Darul Kutub Al ‘Arobi, Beirut.
[10] Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, 11/120, Darul Fikr, cetakan pertama, 1405
[11] Subulus Salam Syarh Bulughil Marom, Muhammad bin Isma’il Ash Shon’ani, Ta’liq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, 4/337, Maktabah Al Ma’arif, cetakan pertama, tahun 1427 H.
[12] Liqo-at Al Bab Al Maftuh, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, kaset 95, no. 19.
[13] Idem.
[14] Mughnil Muhtaj, 4/391.
[15] Idem.
[16] Lihat Mughnil Muhtaj, 4/391.
[17] Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad bin Al Husaini Al Hushni Ad Dimasyqi Asy Syafi’i, hal. 705, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1422 H.
[18] Liqo-at Al Bab Al Maftuh, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, kaset 234, no. 6
[19] Lihat Kifayatul Akhyar,hal. 705.
http://www.rumaysho.com



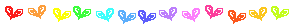

















0 komentar:
Posting Komentar