Siang ini 6 februari 2008, tepatnya di atas jembatan penyebrangan Setiabudi, aku bertemu dua makhluk kecil, kumal, dan berbasuh keringat. Dua sosok kecil kira-kira delapan tahun usianya, menenteng kantong hitam, saat ku menyebrang untuk makan siang, diujung jembatan mereka menawariku tisu. Ya, mereka menjual tisu.
Hanya tisu. Dengan keangkuhan khas penduduk jakarta, aku hanya berisyarat menolaknya tanpa ekspresi. “Terima kasih om” ucap seseorang dari mereka menanggapi dinginya responku. Ah, aku pun merasa belum menyadari akan kemuliaan mereka. Hanya sedikit ku buka senyumku seraya mengangguk kepala.
Kaki-kaki kecil mereka menjelajah lajur lain di atas jembatan, ternyata seorang anak menyapa seorang laki-laki dengan tetap berpolah seorang anak kecil yang penuh keceriaan, laki-laki itupun menolak dengan tiada beda denganku.
Lagi, sayup-sayup ku dengar mereka berucap terima kasih. Kantong hitam tempat tisu dagangan mereka tetap teronggok di sudut jembatan sedikit terbuka tertiup derai angin jakarta. Kulewati dengan lirikan ke dagangan mereka. Dua-pertiganya terisi tisu putih berbalut plastik transparan. Dan aku pun berlalu tanpa goresan kesan.
Setengah jam berlalu, ku seberangi jembatan yang sama kembali. Kudapati mereka tengah mendapatkan pembeli, seorang wanita. Senyum di wajah mereka terlihat berkembang seolah memecah mendung yang sedang manggayut langit Jakarta.
“Terima kasih ya Mbak… semuanya dua ribu lima ratus rupiah” tukas seorang dari mereka. Si wanita tersebut mengulurkan uang sepuluh ribuan.
“Maaf, nggak ada kembaliannya. Ada uang pas nggak Mbak?” Mereka pun menyodorkan kembali uang tersebut. Si wanita pun menggeleng. Sejurus, satu dari mereka menghampiriku. “Om, boleh tukar uang nggak, sepuluh ribuan?”.
Ah, suaranya mengingatkanku pada anak lelakiku yang seusia mereka. Aku pun terhenyak. Ku rogoh saku celanaku, ku cari recehan, yang ku dapatkan hanya empat lembar uang seribuan kembalian dari food court.
“Nggak punya” jawabku.
“Ambil saja kembaliannya, dik!” seru si wanita sambil membalikkan badan dan meneruskan langkahnya ke timur.
Anak ini terkesiap, ia sambar uang empat ribuan di tanganku dan menyampaikan lembar sepuluh-ribuan ke genggamanku. Aku masih berhenti, terdiam, bak kaki terpaku di tempatku berdiri.
Anak ini sontak mengejar wanita tersebut untuk memberikan uang empat ribu tadi. Si wanita kaget. Setengah berteriak ia bilang “Sudah buat kamu saja, nggak apa-apa ambil saja!”
“Maaf mbak, Cuma ada empat ribu, nanti kalau lewat sini lagi saya kembalikan!” Mereka berkeras mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya uang itu pun diterima si wanita karena si kecil segera pergi meninggalkannya.
Tinggallah sepotong episode antara aku dengan mereka. Uang sepuluh ribu di genggamanku tentu bukan sepenuhnya milikku. Mereka pun menghampiriku seraya berujuar, “Om, bisa tunggu ya, saya ke bawah dulu untuk tukar uang ke tukang ojek!”.
“Eeeh… nggak usah… biar aja… nih!” Aku pun mencoba ulurkan uang tersebut. Ia pun menyambar dan berlari menuruni tangga curam jembatan ke kumpulan tukang ojek.
Ku teruskan langkahku, tetapi… “Nanti dulu Om, biar ditukar dulu… sebentar…” Langkahku terhenti.
“Nggak apa-apa, itu buat kalian” Kataku menimpali.
“Jangan… jangan om. Itu uang Om sama Mbak yang tadi juga” kata anak itu bersikukuh pada pendiriannya.
“Sudah, … saya ikhlas, Mbak tadi juga pasti ikhlas!” Ku coba menanggapi.
Namun ia menghalangiku sejenak dan ia berlari ke ujung jembatan dan berteriak memanggil temannya untuk segera bergegas. Secepat kilat, ia pun meraih kantong plastik hitam dagangannya dan berlari ke arahku kembali.
“Ini deh om, kalau kelamaan, maaf…” ia memberi saya delapan pak tisu.
“Buat apa?” Aku pun terbengong.
“Habis teman saya lama sih om, maaf, tukar pakai tisu aja dulu” tukasnya.
Aku pun berusaha untuk mengembalikan meski ia menolaknya. Ku tatap wajahnya, perasaan bersalah muncul pada rona mukanya. Ah, aku kalah set. Ia tetap kukuh menutup rapat tas plastik tersebut.
Beberapa saat aku mematung di sana, sampai temannya kembali dari menukar uang.
Diambil tisu tersebut dari tanganku seraya menukarnya dengan uang milikku, empat ribu rupiah.
“Terima kasih, om!…” Mereka pun kembali ke ujung jembatan. Sayup-sayup ku dengar percakapan di antara mereka.
“Duit mbak tadi gimana?”
“Lu hafal kan orangnya, kali aja ketemu lagi ntar kita kasihin…”
Percakapan itu kemudian menghilang ditelan ramainya lalu-lintas Jakarta. Aku pun terhenyak dan kembali ke kantor dengan beribu perasaan. Ah, betapa mulia hati mereka di usia yang masih sangat muda…
Tuhan… kekuatan kepribadian mereka menaklukkan Jakarta membuatku terenyuh, mereka berbalut baju lusuh, tapi hati dan kemuliaannya sehalus sutra. Mereka mengetahui hak-hak orang lain dan mereka berusaha tidak meminta-minta. Dua anak kecil yang bahkan belum baligh, telah memiliki kemuliaan di usia mereka yang begitu belia.
Ku bandingkan keserakahan kita, yang tak pernah ingin sedikitpun berkurang rizki kita, meski dalam rizki itu bisa jadi sebagian menjadi hak orang lain.
Usia memang tidak menjamin kita menjadi bijaksana. Kitalah yang memilih untuk menjadi bijaksana atau tidak.
(Oleh: Aryadi N, QHSE Manager, BHM Corp, Oil and Gas)
http://addariny.wordpress.com




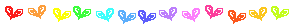

















0 komentar:
Posting Komentar